Dalam sidang Paripurna DPR RI terkait APBN 2026 pada 23 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan intonasi penuh keyakinan menyampaikan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan akan berbasis pada konsep Soemitronomics. Ia merumuskannya dalam tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
Pernyataan tersebut seolah menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia kembali berpijak pada gagasan klasik Soemitro Djojohadikusumo tentang proteksi industri, peran negara dominan, dan substitusi impor. Gagasan yang sempat menjadi pijakan pembangunan ekonomi era 1960-an itu kini didapuk sebagai inspirasi baru. Pertanyaannya: Benarkah resep Soemitro masih relevan dengan struktur mikro dan makro ekonomi Indonesia hari ini?
Konteks global jelas tidak bersahabat. Ekonomi dunia diliputi ketidakpastian akibat perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketegangan geopolitik yang berimbas pada rantai pasok dan tren deindustrialisasi dini di negara berkembang. Indonesia pun tidak kebal. Pada level makro, tekanan datang dari pelemahan rupiah, fluktuasi harga komoditas, potensi defisit transaksi berjalan, dan inflasi yang menekan daya beli masyarakat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB belum pulih optimal setelah pandemi, sehingga ancaman stagnasi industri semakin nyata. Pada level mikro, pelaku usaha masih berhadapan dengan biaya produksi tinggi akibat ketergantungan impor bahan baku, mahalnya logistik dan energi, keterbatasan akses pembiayaan UMKM, rendahnya adopsi teknologi, serta mismatch keterampilan tenaga kerja. Kompleksitas masalah inilah yang menuntut hadirnya kebijakan komprehensif agar pertumbuhan tetap inklusif sekaligus berkelanjutan.
Kembali ke Soemitronomics tentu memberi nuansa historis. Namun, sebagaimana kaset lama yang diputar ulang, resep ini bukan tanpa risiko. Proteksi industri memang bisa memberi ruang tumbuh bagi sektor domestik, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan inefisiensi pasar, mengganggu keunggulan komparatif, dan menciptakan distorsi harga akibat perlindungan berlebihan.
Data menjadi pengingat penting. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia tahun 2023 tercatat 6,33, lebih tinggi dibanding Vietnam (4,6) dan Malaysia (4,5). Artinya, Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan output yang sama. Dalam kondisi efisiensi serendah itu, tarif proteksi justru memperburuk daya saing karena produk domestik tetap kalah di pasar ekspor meski dilindungi.
Lebih jauh, data periode 2012–2020 menunjukkan fenomena anomali pada 24 subsektor manufaktur: peningkatan efisiensi justru beriringan dengan turunnya penyerapan tenaga kerja. Ini membuka ruang kritik yang serius. Pertama, proteksi berlebihan memang dapat melindungi produk lokal, tetapi sekaligus mengisolasi industri dari kompetisi global sehingga tidak terdorong melakukan inovasi, efisiensi, dan optimalisasi skala ekonomi. Kedua, perilaku rent-seeking mudah tumbuh ketika perusahaan tertentu, baik BUMN maupun swasta, menikmati perlindungan pasar tanpa akuntabilitas. Ketiga, monopoli dan oligopoli di sektor strategis seperti energi, perbankan, dan bahan baku berisiko membatasi persaingan, menaikkan harga bagi konsumen, dan menghalangi masuknya pelaku baru yang lebih inovatif.
Dari sisi perdagangan internasional, proteksi juga rentan menimbulkan dilema. Produk domestik yang masih mahal sulit bersaing meski tarif impor dinaikkan. Kritik dari perspektif ekonomi kelembagaan bahkan lebih tajam. Efektivitas kebijakan proteksionis sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola negara. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kelembagaan, proteksi mudah berubah menjadi instrumen rente politik.
Sejarah menunjukkan bahwa proteksi dan intervensi negara kerap dimanfaatkan oleh elite untuk memperkuat posisi ekonomi sekaligus politik. Akibatnya, akses terhadap sumber daya, kredit, dan izin usaha terkonsentrasi pada segelintir pihak, sedangkan pelaku ekonomi lain tersisih. Pola inilah yang kemudian melahirkan oligarki ekonomi, suatu ironi ketika kebijakan proteksi justru memperlebar ketimpangan.
Institusionalisme menegaskan bahwa proteksi hanya akan efektif bila disertai reformasi kelembagaan yang serius. Tanpa memperkuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), meningkatkan integritas birokrasi, dan memperluas akses pasar serta pembiayaan bagi UMKM, kebijakan ala Soemitronomics hanya akan memperbesar risiko munculnya rente, monopoli, dan kartel. Proteksi yang tidak diiringi pembenahan institusi justru berpotensi mereproduksi struktur ekonomi timpang dan oligarkis, bukannya menciptakan daya saing berkelanjutan.
Namun, menilai Soemitronomics tidak cukup hanya dari sisi kelemahan. Gagasan ini memang lahir dari semangat mempercepat industrialisasi, menjaga kedaulatan ekonomi, dan menciptakan ruang tumbuh bagi industri domestik yang belum siap bersaing di pasar bebas.
Dibanding p...

 15 hours ago
2
15 hours ago
2


















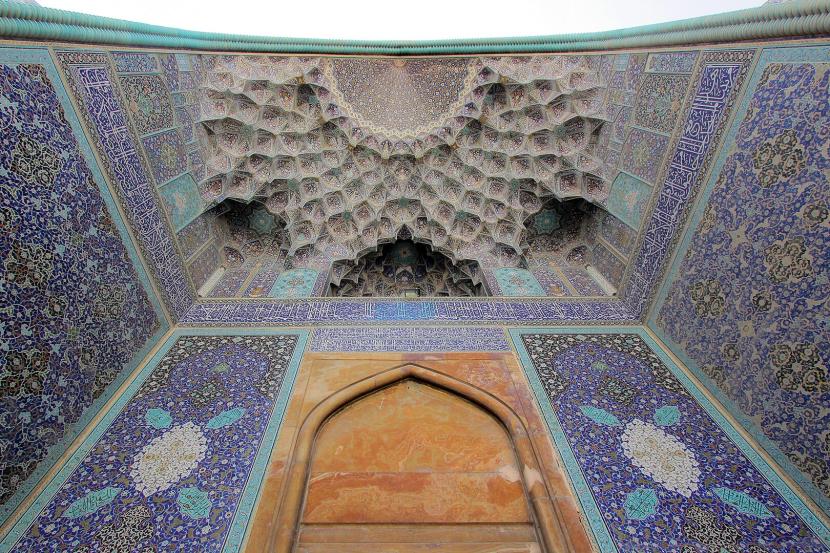

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4667381/original/034639800_1701238155-Planet_Uranus.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2704247/original/044238300_1547530681-Bendera_China.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5316351/original/043054100_1755233091-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5259703/original/093147300_1750480802-Screenshot_2025-06-21_113714.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5319656/original/077838000_1755570078-Pandi.jpeg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4701138/original/017132500_1703816043-GCU6VThaoAAm5dA.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5137008/original/041672900_1739896421-Anak_demam.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5321429/original/097772500_1755672753-WhatsApp_Image_2025-08-20_at_13.29.47__4_.jpeg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5311932/original/009433500_1754900053-Oak_Ridge_National_Laboratory.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)

